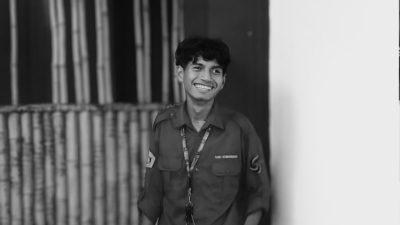Oleh: Mochdar Soleman, S.IP., M.Si
Dosen dan Pengamat Politik Lingkungan Universitas Nasional | Sekjen GP Nuku
Pada artikel sebelumnya, saya menyoroti kasus penangkapan 11 warga Maba Sangaji di Halmahera Timur dalam perspektif dimensi moral dan politik hukum “bagaimana hukum menjadi alat kekuasaan yang menekan masyarakat adat.” Sementara, artikel ini memperluas analisisnya melalui perspektif demokrasi dan politik civil society, agar persoalan ini tidak hanya dibaca sebagai konflik hukum, melainkan sebagai gejala menyusutnya demokrasi lokal di wilayah sumber daya.
Penangkapan 11 warga Maba Sangaji di Halmahera Timur pada pertengahan Mei 2025 bukan sekadar kasus hukum. Ia merupakan gejala struktural dari demokrasi yang kehilangan akar sosialnya. Negara tampak hadir, tetapi kehilangan makna keberpihakan. Ketika warga adat yang melakukan ritual adat dan protes lingkungan justru ditangkap, kita sedang menyaksikan demokrasi yang tidak lagi menegakkan partisipasi, melainkan ketundukan.
Demokrasi yang Menyusut di Daerah Sumber Daya
Kekuatan demokrasi di Indonesia sering diukur dari kelancaran pemilu dan pergantian kekuasaan. Namun, demokrasi sejati diuji di tingkat lokal, terutama di daerah kaya sumber daya seperti Maluku Utara. Di wilayah ini, demokrasi mudah tergelincir menjadi formalitas birokrasi ketika bersentuhan dengan kepentingan modal dan korporasi ekstraktif.
Konflik tambang di Halmahera Timur bukanlah persoalan baru. Di balik pembangunan smelter dan proyek strategis nasional, masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah, air, dan ruang hidupnya. Ketika aspirasi mereka tidak tertampung melalui mekanisme politik formal, yang tersisa hanyalah jalan sosial “aksi, ritual, dan symbol”. Ironinya, ekspresi sosial ini justru dibungkam dengan pendekatan hukum dan keamanan.
Kasus Maba Sangaji memperlihatkan bagaimana hukum kehilangan daya emansipatorisnya. 11 warga yang memperjuangkan hak lingkungan ditangkap dengan tuduhan “premanisme” dan “penguasaan lahan tanpa izin”, padahal yang mereka pertahankan adalah hutan adat dan sungai yang menjadi sumber kehidupan. Hukum, yang seharusnya menjadi perisai warga, berubah menjadi alat penyeragaman kepentingan negara dan modal.
Negara dan Monopoli Kekerasan
Max Weber, dalam analisis klasiknya, menyebut negara sebagai lembaga yang memonopoli penggunaan kekerasan yang sah. Namun, dalam konteks demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak berhenti pada legalitas, melainkan harus disertai etika moral dan tanggung jawab sosial. Ketika aparat menggunakan kekuasaan negara untuk mengkriminalkan ekspresi rakyat, monopoli kekerasan itu kehilangan legitimasi.
Di Halmahera Timur, negara seolah lupa bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjamin kehidupan yang beradab. Ketika hukum diterapkan tanpa empati, negara berubah menjadi mesin administratif yang dingin. Penegakan hukum tanpa keadilan sosial hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara warga dan negara.
Demokrasi kehilangan maknanya ketika hukum berhenti pada teks dan tidak lagi menyentuh konteks. Tindakan warga Maba Sangaji bukan kriminalitas, melainkan ekspresi politik masyarakat adat dalam menuntut hak partisipasi atas sumber daya mereka. Dalam bahasa Weber, ini adalah contoh ketika rasionalitas formal hukum mengalahkan rasionalitas substantif moral. Negara tampak modern secara prosedural, tapi kosong secara etik.
Momen Politik yang Luar Biasa
Andreas Kalyvas, dalam Democracy and the Politics of the Extraordinary, menjelaskan bahwa demokrasi sejati lahir dari momen-momen luar biasa, ketika rakyat mengambil alih ruang politik yang selama ini dimonopoli oleh elit. Dalam momen seperti itu, warga biasa menantang status quo dan menuntut koreksi terhadap institusi negara.
Aksi masyarakat Maba Sangaji seharusnya dibaca sebagai extraordinary politics, upaya warga untuk mengembalikan politik kepada rakyat. Ketika negara justru menjawabnya dengan tindakan represif, maka demokrasi kehilangan kemampuan korektifnya. Proses hukum terhadap warga bukan hanya kriminalisasi individu, tetapi pemadaman terhadap potensi demokratis yang tumbuh dari bawah.
Negara yang sehat seharusnya mampu mengubah konflik menjadi koreksi. Sebaliknya, negara yang rapuh justru mengubah koreksi menjadi ancaman. Ketika setiap ekspresi politik warga dibalas dengan kekerasan hukum, demokrasi berhenti menjadi ruang negosiasi dan berubah menjadi arena kontrol.
Civil Society yang Terdesak
Sung Ho Kim, dalam Max Weber’s Politics of Civil Society, menekankan bahwa civil society adalah fondasi kehidupan politik yang sehat. Ia menjadi ruang antara “penghubung antara negara dan warga” tempat individu belajar mengorganisir kepentingan bersama dan mengontrol kekuasaan.
Namun, di wilayah-wilayah tambang seperti Halmahera, ruang civil society justru terdesak. Komunitas adat, organisasi lingkungan, dan lembaga lokal yang seharusnya menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah justru dikriminalkan atau dilemahkan. Ketika asosiasi sipil dibungkam, negara kehilangan instrumen komunikasi sosialnya.
Hal inilah yang menjelaskan mengapa konflik tambang di Maluku Utara terus berulang “tidak ada mekanisme dialog yang diakui, tidak ada lembaga sipil yang dihormati, dan tidak ada kebijakan partisipatif yang dijalankan.” Negara hanya mengenal dua aktor yakni aparat dan perusahaan, disisi lain warga adat diposisikan sebagai gangguan terhadap investasi. Ini bukan sekadar ketimpangan ekonomi, tapi krisis representasi demokrasi.
Krisis Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Politik
Kepemimpinan daerah menjadi titik krusial dalam situasi seperti ini. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memikul tanggung jawab politik untuk memastikan demokrasi lingkungan berjalan. Pemerintah provinsi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan modal, melainkan pelindung kepentingan publik.
Kebijakan tambang harus dikembalikan ke prinsip tata kelola yang adil: audit independen terhadap izin pertambangan, evaluasi dampak ekologis, dan pembentukan forum konsultasi publik berbasis adat. Gubernur juga perlu memperkuat mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai prasyarat izin usaha, agar masyarakat adat tidak lagi menjadi korban dari kebijakan yang diputuskan tanpa persetujuan mereka.
Tindakan-tindakan seperti itu tidak hanya bersifat administratif, tapi juga moral. Kepemimpinan yang sejati ditunjukkan bukan oleh keberanian menandatangani izin, tetapi oleh keberanian menolak ketika izin itu melukai keadilan sosial.
Menata Ulang Relasi Negara, Modal, dan Warga
Konflik Maba Sangaji menunjukkan bahwa relasi antara negara, modal, dan masyarakat membutuhkan desain ulang. Negara harus menegakkan kembali fungsinya sebagai wasit, bukan sekutu salah satu pihak. Hubungan antara hukum, investasi, dan masyarakat perlu disusun ulang berdasarkan prinsip keadilan distributif.
Penegakan hukum tidak boleh hanya berpihak pada stabilitas investasi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekologi. Ketika warga membela tanah dan air, mereka sebenarnya sedang membela kepentingan jangka panjang bangsa ini. Dalam perspektif Weberian, rasionalitas pembangunan yang hanya mengejar efisiensi ekonomi tanpa memperhitungkan nilai kemanusiaan akan membawa kita ke dalam “kandang besi” rasionalitas instrumental — masyarakat modern yang kehilangan arah moralnya.
Kita harus belajar bahwa hukum yang benar bukan yang hanya menegakkan aturan, tetapi yang melindungi nilai hidup bersama. Demokrasi tidak bisa berjalan di atas penderitaan masyarakatnya sendiri.
Membangun Demokrasi yang Berakar
Penyelesaian kasus Maba Sangaji seharusnya dijadikan momentum memperkuat demokrasi lokal. Pertama, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap izin tambang di Halmahera Timur dan seluruh Maluku Utara untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip lingkungan dan hak masyarakat adat. Kedua, membangun forum multi-pihak di tingkat provinsi yang melibatkan komunitas adat, akademisi, dan pemerintah untuk merumuskan tata kelola sumber daya yang transparan. Ketiga, memastikan perlindungan hukum bagi pembela lingkungan sebagai bagian dari hak sipil dan politik.
Tanpa langkah-langkah itu, demokrasi di daerah sumber daya hanya akan menjadi bayangan dari pusat kekuasaan. Negara mungkin masih tampak kuat, tapi sesungguhnya rapuh karena kehilangan akar legitimasi dari rakyatnya sendiri.
Demokrasi yang Takut pada Rakyatnya Sendiri
Kasus Maba Sangaji seharusnya menggugah kita semua untuk bertanya ulang, demokrasi macam apa yang kita bangun jika warga yang memperjuangkan hak hidup justru dijebloskan ke penjara? Demokrasi yang takut pada rakyatnya sendiri bukanlah demokrasi, melainkan bentuk baru otoritarianisme yang bersembunyi di balik bahasa hukum.
Hukum yang adil tidak mungkin hidup dalam sistem yang menutup telinga terhadap keadilan sosial. Demokrasi yang kokoh tidak mungkin tumbuh dari tanah yang dipenuhi ketakutan. Jika negara ingin bertahan sebagai institusi yang sah, maka ia harus kembali berpihak pada yang paling dasar: manusia dan lingkungannya.
11 warga Maba Sangaji hanyalah potret kecil dari luka besar yang diderita demokrasi kita. Luka itu hanya bisa sembuh jika negara berani melihat ke cermin, bukan mencari kambing hitam.