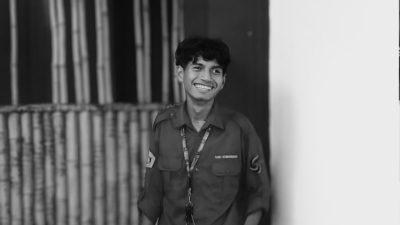Oleh Mochdar Soleman
Dosen dan Pengamat Politik Lingkungan – Universitas Nasional
Pada Juni 2025, Kementerian Dalam Negeri menetapkan sebuah keputusan melalui Kepmendagri No. 300.2.2-2138 yang memindahkan empat pulau diantaranya; Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah. Di mata birokrasi pusat, ini sekadar koreksi administratif. Tapi bagi masyarakat Aceh Singkil, ini pemindahan paksa sejarah, spiritualitas, dan kedaulatan wilayah.
Jika hal demikian di tinjau dalam perspektif studi politik lingkungan, ini bukan hanya sekedar “perbaikan peta,” melainkan penaklukan spasial. Negara menjadi aktor dominan yang menggunakan instrumen administratif untuk melakukan rekayasa penyusunan ulang ruang secara sepihak, menghapus narasi lokal, dan memberi ruang baru pada kepentingan dominan.
Betapa tidak, kepmendagri ini membuktikan bahwa peta bukan dokumen netral. Ia bisa disebut sebagai alat kuasa. Dalam perspektif ekologi politik mengutip Bryant & Bailey dalam Third World Political Ecology, penguasaan ruang oleh negara di dunia selatan sering dikendalikan oleh elite pusat dengan justifikasi administratif, demi kepentingan pertambangan, perikanan, atau investasi pariwisata.
Ditarik dalam persoalan yang ada saat ini, potensi geopolitik dan ekonomi kelautan pulau-pulau kecil tersebut baik dilihat dari zona tangkap ikan, peluang pelabuhan pesisir menjadi konteks tersembunyi di balik penghapusan administratif. Kita tidak melihat ada studi lingkungan, tidak melihat ada publikasi BIG dan tidak meilhat ada konsultasi public yang disampaikan, yang kita lihta hanyalah keputusan sepi yang mengguncang batas dan identitas.
Kita coba menelusuri melalui pendekatan “akses” mengutip Ribot & Peluso (2003, 153) “Access is the ability to benefit from things—including material objects, persons, institutions, and symbols.” yang menegaskan bahwa hak atas ruang bukan hanya soal legalitas formal, melainkan juga soal siapa yang punya kuasa menentukan, mengatur, dan mendapatkan manfaat. Negara, dalam hal ini, telah merampas akses masyarakat lokal bukan hanya atas pulau, tetapi atas masa depan mereka.
Kita dapat melihat contoh yang ditunjukkan Erwiza Erman dalam studinya tentang politik lingkungan di Bangka, negara cenderung memihak korporasi dan elite lokal yang beraliansi dengan pusat, dengan menyisihkan komunitas lokal dari proses perencanaan dan distribusi manfaat. Pola itu berulang di Singkil hari ini.
Perlu kita sadari Bersama bahwa pulau-pulau itu bukan titik kosong di koordinat. Mereka bagian dari sejarah perjuangan panjang rakyat Singkil sejak 1957, ketika PAPKOS (Rezza, 2008, 35-37) dibentuk untuk memperjuangkan status otonomi wilayah. Mereka adalah ruang zikir laut, kenduri adat, dan simbol dari keberadaan Aceh di peta Indonesia.
Kita ketahui Bersama bahwa Monumen negara yang dibangun di Pulau Panjang tahun 2012 bukan sekadar tugu administratif. Ia lambang legitimasi sejarah. Maka, penghapusan pulau-pulau ini bukan sekadar pengurangan luas wilayah, tetapi upaya pelurusan ulang sejarah oleh negara.
Mengutip apa yang dikemukakan dan diamini mentri Kebudayaan, Fadli Zon dalam komentarnya, “Singkil itu bukan sekadar wilayah. Ia adalah ruh Indonesia.” Ia adalah tempat bahasa, budaya, dan sejarah bercampur dalam harmoni kebangsaan.
Jika kita cermati dalam perspektif Michel Foucault, kita bisa melihat fenomena sovereign cartography, negara menentukan eksistensi berdasarkan garis peta. Siapa yang di dalam, hidup; siapa yang di luar, hilang. Dalam konteks ini, pulau yang dihapus adalah rakyat yang dikeluarkan dari wacana kenegaraan.
Ini adalah ekspresi dari kolonialisme internal, dimana kekuasaan pusat yang menaklukkan pinggiran bukan dengan senjata, tapi dengan pena birokrasi. Sebuah bentuk kekerasan yang steril, tapi mematikan secara identitas.
Tentu nya kita ketahui dalam konteks ekologi, bahwa Pulau kecil memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung abrasi, habitat laut, dan sumber kehidupan pesisir. Tanpa audit lingkungan, keputusan ini membuka peluang eksploitasi ekologis yang berbahaya. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa keputusan administratif yang mengabaikan dimensi ekologi bisa menghasilkan kehancuran berlapis baik dari aspek sosial, lingkungan, dan budaya.
Keputusan yang diambil oleh Mendagri jelas bertolak belakang dengan Pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 23/2014 jelas mensyaratkan bahwa perubahan batas wilayah harus melalui persetujuan DPRD dua provinsi, partisipasi publik, dan publikasi terbuka. Namun dalam persoalan ini seprti terlihat tidak satu pun dijalankan. Negara bertindak seolah peta adalah ruang kosong yang bisa digambar ulang tanpa akuntabilitas.
Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengingkaran terhadap semangat desentralisasi dan demokrasi spasial. Ketika kekuasaan menggambar peta tanpa rakyat, maka demokrasi hanya formalitas tanpa isi.
Empat pulau telah dihapus dari peta Aceh. Tapi sejarah rakyat Aceh Singkil tak bisa dihapus dari hati mereka. Mereka akan terus menyebut nama pulau itu dalam zikir, dalam adat, dalam doa, dan dalam perlawanan.
Oleh karenanya, tidak ada kata lain selain Cabut Kepmendagri No. 300.2.2-2138 dan lakukan audit geospasial terbuka bersama BIG, DPRD dua provinsi, dan masyarakat adat, tegakkan prinsip keadilan spasial dan partisipasi public serta hentikan kekerasan administratif atas nama pembangunan.
“Karena peta yang digambar tanpa rakyat adalah peta yang akan dilawan oleh sejarah.”